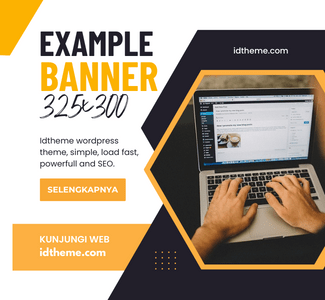LAPORAN HUKUM DAN HAM 2018 dan PROYEKSI 2019
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
20 TAHUN REFORMASI:
RAKYAT DI BAWAH KUASA MODAL DAN PENGUASA
Jakarta, Gramediapost.com
Selama tahun 2018, hukum dan kebijakan di Indonesia diwarnai dengan masih banyaknya kriminalisasi terhadap masyarakat yang tengah memperjuangkan hak-haknya. Hal ini terjadi di semua sektor, seperti sumber daya alam, lingkungan hidup, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berekspresi, kriminalisasi buruh, dan kriminalisasi terhadap kelompok minoritas dan rentan. Hal ini disebabkan masalah-masalah terkait hukum dan kebijakan:
Pertama, adanya pasal-pasal kriminalisasi dalam beberapa UU seperti UU ITE (Pasal 27 ayat (3), pasal 28 (2), KUHP (pasal 310, 311, 315, 156, 156a, 167, 168, 200, 201, 212 (10), UU No. 1/PNPS/1965, UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, UU No. 18/2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan UU No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Memasuki Tanah Orang Lain Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.
Kedua, sistem hukum acara pidana yang mempermulus kriminalisasi, karena hal-hal sebagai berikut:
minimnya akuntabilitas penentuan tersangka (misalnya, tidak ada batasan dalam penentuan tersangka)
tersangka/terdakwa tidak segera diperiksa/diadili (undue delay)
ketiadaan habeas corpus
mengejar pengakuan terdakwa
akuntabilitas penahanan
penahanan berkepanjangan
hak penasehat hukum yang dibatasi
Ketiga, kosongnya pasal pemidanaan penyiksaan dan pemulihan.
Keempat, tidak adanya reforma agraria sejati. Konfllik-konflik agraria yang ditangani kantor-kantor LBH tidak tersentuh, karena hanya tanah-tanah yang tergolong clean and clear yang diurus. Artinya, tanah-tanah konflik yang bersertifikat HGU, tanah HGU terlantar yang belum dilepaskan pemiliknya, tidak menjadi obyek reforma agraria. Demikian juga tanah-tanah petani yang dahulu dirampas BUMN seperti PTPN dan Perhutani tidak tersentuh dan tidak ada mekanisme penyelesaiannya selain skema Perhutanan Sosial.
Kelima, ketiadaan Standar Berujung Pada Skorsing Mahasiswa & Syarat Diskriminatif
Kampus menggunakan pasal 63 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi untuk melakukan skorsing tanpa standar dan due process of law. Hal yang sama terjadi terhadap proses penyaringan penerimaan mahasiswa yang memasukkan ketentuan-ketentuan diskriminatif seperti kondisi disabilitas maupun orientasi seksual ataupun identitas gender.
Keenam, kebijakan infrastruktur yang menggusur. Di luar debat tentang hutang yang sangat besar yang digunakan untuk infrastruktur, terdapat hal lain yaitu untuk kepentingan siapa utamanya infrastruktur ini dibangun? Siapa yang akan paling mendapatkan keuntungan, apakah orang atau bisnis? Saat ini proyek-proyek infrastruktur terutama megaproyek banyak menggusur rumah, lahan pertanian atau perkebunan dan pekerjaan. Hal ini paradoks dengan jargon pembangunan infrastruktur yaitu meningkatkan perekonomian. Penggusuran ini malah menyebabkan masyarakat menjadi miskin setidaknya berkurang kesejahteraannya. Debat paling mendasar sebenarnya terletak pada hak atas pembangunan. Pembangunan model apa yang dikehendaki rakyat? Apakah pembangunan selalu harus diidentikkan dengan pusat perbelanjaan megah, jalan tol, jalan layang dan pabrik di mana-mana? Di mana tempat bagi model pembangunan yang banyak ruang terbuka hijau, jalan-jalan yang dapat dilalui sepeda dan pejalan kaki, serta air mengalir di mana-mana?
Ketujuh, kosongnya UU Penghapusan Kekerasan Seksual.
Indonesia menggantungkan pemberantasan kekerasan seksual melalui KUHP yang sudah berumur 100 tahun. Meskipun untuk tindak kekerasan seksual yang ditemukan belakangan seperti kekerasan dalam rumah tanggal dan perdagangan perempuan telah ada pengaturannya, tetapi kekerasan seksual yang menjadi dasar seperti perkosaan definisinya sangat tertinggal dan karenanya tidak mencukupi untuk menjaring fenomena yang ada. Perkosaan di dalam KUHP diatur dalam Pasal 285 dan hanya mencakup penetrasi antara laki-laki kepada perempuan. Artinya pemaksaan oral sex ataupun memasukkan benda-benda selain alat kelamin tidak dihitung sebagai perkosaan.
Kedelapan, adanya pasal-pasal penghambat kebebasan sipil.
UU 16/2017 tentang Penetapan Perpu Ormas yang mengandung beberapa masalah khususnya dalam mengatur kriteria organisasi terlarang atau separatis, menggunakan nama, lambing, bendera, atau symbol organisasi, pencabutan status badan hukum Ormas, dan adanya frasa “penistaan agama”, masalah pemidanaan penodaan agama, dan farasa “tindakan permusuhan”.
PP 60/2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik
Meskipun Pasal 2 menyatakan ruang lingkup peraturan pemerintah ini adalah kegiatan keramaian umum atau kegiatan masyarakat lainnya dan pemberitahuan kegiatan politik, kepolisian kerap menggunakan aturan ini untuk membatasi aksi atau demonstrasi. Pasal 3 PP 60/2017 menyebutkan jelas apa yang dimaksud kegiatan keramaian umum yaitu: eramaian, tontonan untuk umum, dan arak-arakan di jalan umum.
Sedangkan pasal 4 memang mengatur hal yang begitu tidak jelas yaitu “bentuk kegiatan masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi kegiatan yang dapat membahayakan keamanan umum sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”. Apabila kita kaitkan aturan ini dengan peraturan yang sudah ada yaitu UU 9/1998 maka jelas apa-apa yang sudah diatur dalam UU 9/1998 tidak dapat menjadi subyek PP 60/2017. Mengambil apa-apa yang menjadi subyek UU 9/1998 menjadi subyek PP 60/2017 artinya membuat UU tunduk kepada PP, sesuatu yang bertentangan dengan asas hukum.
RKUHP
Kesembilan, adanya Qanun 6/2014 tentang Jinayah.
Masalah dalam Qanun Jinayah sendiri dapat dikategorisasi menjadi:
Pihak yang terkena
Orang non-muslim dapat menjadi subyek qanun Jinayat ini yaitu : orang non-Muslim yang melakukan tindak pidana (jarimah) bersama-sama dengan warga Aceh beragama Islam dan non-Muslim itu memilih dan menyatakan tunduk sukarela pada Qanun Jinayah. Orang muslim yang bukan orang Aceh otomatis juga menjadi subyek qanun jinayah saat ia berada di Aceh. Padahal apabila ia berada di luar Aceh, untuk tindak pidana yang tidak ada dalam KUHP maka ia tidak akan kena tindak pidana. Adanya dualisme hukum pidana ini jelas merupakan masalah serius.
Tindak Pidana yang Tidak Ada dalam KUHP
Terdapat jenis-jenis tindak pidana dalam qanun yang tidak ada dalam KUHP/hukum pidana nasional yaitu: ikhtilath, khalwat, liwath, musahaqah, qadzaf, minum khamar.
Tindak pidana tentu tidak boleh diatur dalam peraturan daerah, apalagi yang tidak ada dasarnya di hukum pidana nasional.
Hukum Acara
Hukum acara tersebut ada beberapa hal yang bertentangan dengan hukum acara pidana UU No. 8/1981 (KUHAP).
Bentuk Hukuman
Pencambukan apalagi yang dipertontonkan merupakan bentuk penghukuman yang kejam, tidak manusia maupun merendahkan martabat manusia.
Kesepuluh, masalah perbudakan modern. Persoalan perburuhan sebenarnya lebih dari masalah yang ada di dalam pabrik atau industri. Ia berawal dari pembukaan kawasan industri demi mempercepat terbentuknya kota. Banyak narasi yang menyertai pembukaan kawasan industri ini. Salah satunya adalah membuka lapangan pekerjaan. Padahal, ada jutaan orang yang termiskinkan karena terampas ruang hidup di kampungnya bermigrasi ke kota. Data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menunjukan pada tahun 2014 ada 74 kawasan industri dengan mencapai luas lahan 36.300 ha, pada 2017 jumlah kawasan industri melonjak menjadi 87 dengan luas mencapai 59.700 ha. Selama ini Pulau Jawa menjadi pusat pertumbuhan termasuk dalam skema pembangunan ekonomi ia dijadikan sebagai koridor ekonomi pusat industri dan jasa. Kenyataannya, jumlah kawasan industri di luar Jawa mengalami lonjakan yang cukup besar. Pembukaan kawasan industri nyaris selalu dijadikan satu-satunya strategi pengurus negara baik di tingkat lokal maupun di tingkat pusat untuk membuka lapangan kerja. Mereka menyatakan hal ini sebagai upaya paling cepat untuk menanggulangi kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik jumlah angkatan kerja pada Februari 2018 sebanyak 133,94 juta orang, naik 2,39 juta orang dibanding Februari 2017. Merujuk pada penjelasan Menteri Perindustrian, tahun 2016 jumlah pekerja Industri di Indonesia sebanyak 15.975.086 orang. Sebanyak 73,98 juta orang (58,22%) penduduk Indonesia bekerja di kegiatan informal, dari 127,07 Juta orang yang bekerja, sebesar 7,64 % masuk katagori setengah menganggur dan 23,83% pekerja paruh waktu. Dalam setahun terakhir setengah penganggur dan pekerja paruh waktu naik 0,02% dan 1,31%.
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kawasan industri ternyata tidak mampu menjawab pemenuhan lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, narasi yang diciptakan tentang memperluas kawasan industri untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan pengangguran perlu ditelisik lebih mendalam. Perbedaan yang mencolok antara angkatan kerja dengan pekerja industri menunjukan bahwa pekerja di sektor informal memiliki angka yang sangat tinggi. Masalah terbesar dari pekerja informal adalah informalisasi hubungan kerja mengakibatkan hilangnya tanggung jawab baik dari pemberi kerja maupun dari pemerintah. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan komplain atau keberatan atas ketimpangan relasi industrial.
Pembukaan kawasan industri, memiliki banyak aspek di antaranya adalah:
Alih fungsi lahan
Pembukaan kawasan industri selama ini tidak dilakukan di perkotaan, melainkan di pinggiran kota. Hal ini mengubah menjadi wilayah urban dengan berbagai persoalan yang berkelindan di dalamnya. Kota merupakan etalase dan showroom tempat dilakukannya pemasaran. Sementara produksi dilakukan di pinggiran namun tetap dengan berbagai infrastruktur penunjang seperti jalan tol, bandara atau pelabuhan, pembangkit energi dan lain sebagainya.
Perampasan Tanah
Karena kawasan industri membutuhkan lahan maka tidak menutup kemungkinan pembangunannya diawali dengan perampasan tanah. Perampasan tanah dari penduduk lokal dan petani-petani maupun petani penggarap dengan harga yang murah. Apalagi bagi petani-petani penggarap yang menggarap di atas tanah-tanah Negara. Setelah tanah tidak lagi dimiliki dan industri terbangun, bekerja menjadi buruh adalah pilihan yang sulit terelakkan. Pilihan lainnya adalah menjadi pekerja rumah tangga atau pekerja migran. Dalam bekerja ini berbagai pelanggaran hak hingga mengarah pada perbudakan modern kerap muncul. Pelapor Khusus Bentuk Baru Perbudakan Termasuk Sebab dan Konsekuensinya (Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its causes and consequences) pertama kali dipilih pada Mei 2014. Di Indonesia kondisi dan bentuk kerja yang buruk ditemukan sebagai berikut:
Rezim upah murah
Salah satu daya tarik investasi yang diandalkan pemerintah Indonesia adalah upah murah. Hal ini tercermin dari masalah upah yang menjadi masalah rutin tahunan, dipersoalkan oleh kaum buruh. Setiap akhir tahun buruh dan pemerintah berdebat mengenai penetapan upah minimum hampir di setiap wilayah di Indonesia. Upah minimum semakin rumit dalam upah minimum sektoral. Rata-rata sektor garmen memiliki UMPSP/K yang paling rendah. Akibat distigma sebagai pekerjaan dengan ketrampilan rendah. Stigma ini muncul karena asumsi ketrampilan jahit-menjahit ini umumnya dimiliki perempuan tanpa perlu belajar.
Diberlakukannya PP 78/2015 membuat ketentuan upah minimum menjadi lebih buruk. Salah satunya Pasal 43 (1) yang membuat upah minimum tidak hanya didasarkan atas kebutuhan hidup layak atau tetapi “dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”. Kemudian Pasal 43 (5) membuat komponen untuk menentukan kebutuhan hidup layak hanya dapat ditinjau dalam jangka waktu 5 tahun. Masalah lain adalah pasal 43 (7) mengatur “kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional menggunakan data dan informasi yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik”. Artinya ada dominasi tentang data dan informasi. Padahal bukan tidak mungkin data dan informasi di suatu pasar berbeda dengan pasar lainnya.
PP 78/2015 mengekalkan kritik lama terhadap upah minimum yaitu hanya mengakomodir buruh lajang khususnya pasal 43 (2) yang berbunyi “kebutuhan hidup layak sebagaimana merupakan standar kebutuhan seorang Pekerja/Buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 bulan”.
Sistem kerja yang menyengsarakan
Di samping upah murah, sistem kerja yang menyengsarakan buruh juga berlaku di dalam hubungan industrial. Misalnya dalam sektor garmen saat ini lebih banyak perusahaan menerapkan sistem kerja target yang mengutamakan capaian produksi. Jadi seseorang bekerja tidak ditetapkan oleh jam kerja, melainkan ditetapkan berbasiskan pada jumlah produksi. Hal ini mengakibatkan jam kerja tidak menentu, tetapi umumnya lebih panjang dari biasanya. Selanjutnya adalah menghilangkan upah lembur, karena basis kesepakatannya bukan jam kerja melainkan target produksi. Beberapa kondisi perusahaan yang menerapkan sistem kerja target ini sedemikian buruk sehingga terindikasi perbudakan modern.
Menginformalkan Hubungan Kerja
Sebagaimana Letter of Intent Indonesia kepada IMF pada tanggal 18 Maret 20113 kebijakan perburuhan di Indonesia diarahkan pada pasar tenaga kerja yang lentur (Flexibility Labour Market). Hal ini dapat kita lihat pada Memorandum of Economic and Financial Policies Government of Indonesia and Bank Indonesia bagian Labor Policies (kebijakan perburuhan) poin 42. Paket 3 UU Perburuhan diperuntukkan untuk memudahkan hal ini. Misal UU 13/2003 adalah undang-undang pertama yang melegalkan hubungan kerja kontra & outsorcing yang merupakan dukungan utama untuk pasar tenaga kerja yang lentur. Tujuannya tentu untuk meminimalisir ongkos produksi.
Keberadaan kawasan industri membutuhkan penopang-penopang lainnya misal pembangunan infrastruktur atau bisnis properti. Pembangunan property dan infrastruktur membutuhkan orang-orang yang bersedia menjadi kuli bangunan dengan sistem pembayaran bermacam-macam, bisa kuli harian atau kuli borongan. Namun kuli-kuli ini adalah para pekerja yang pada umumnya bisa dikatagorikan sebagai pekerja informal karena tidak ada kesepakatan kerja dengan upah yang murah karena dinilai menggunakan ketrampilan yang rendah. Belum lagi sistem pembayaran harian atau borongan, yang pasti kebanyakan mereka adalah pekerja musiman serta bekerja berdasarkan pada target waktu yang telah ditetapkan oleh sang pengusaha. Untuk melengkapi semua cerita di atas, bahwa saat ini juga menjamur aparteman yang juga mempekerjakan pekerja-pekerja sektor rumah tangga yaitu cleaning service, tukang cuci, tukang kebun, supir, pekerja mini market, dan pekerja pada usaha kecil-kecilan lain seperti warnet, dll. Menyisakan cerita tentang kerumitan bagi pekerja-pekerja sektor informal.
Meluasnya industri Pekebunan seperti kelapa sawit, teh, maupun perkebunan lainnya juga menyisakan cerita tentang buruh harian lepas, atau pekerja bulanan dengan upah yang sangat murah, kondisi kerja buruk serta kesehatan dan keselamatan kerja yang tidak terjamin. Intinya semua didorong untuk menjadi pekerja, baik pekerja industri, jasa maupun sektor informal dengan cara menghilangkan daulat rakyat atas sumber-sumber agraria.
Pekerja Rumahan
Pekerja rumahan (home-based worker) adalah bentuk hubungan kerja yang diciptakan dalam semangat flexibility labour market untuk mempermudah industri dan melipatgandakan keuntungan dengan cara mengurangi ongkos produksi. Pekerja rumahan sering disalahartikan sebagai pemborong pekerjaan. Hal ini karena mereka mengerjakan pekerjaannya di rumah dengan target jumlah barang tertentu. Sebagian besar pekerja rumahan adalah perempuan. Dan pada akhirnya pekerjaan tersebut menjadi dikerjakan secara bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain. Dengan skema pekerja rumahan seperti ini maka waktu bekerja menjadi tidak terbatas karena pembatasnya adalah target. Karena pada umumnya upah per barang sangat kecil maka pekerja rumahan akan memaksakan diri untuk menghasilkan jumlah yang banyak agar upahnya menjadi cukup. Selain itu sebenarnya pekerja rumahan mensubsidi perusahaan karena listrik, air dan tempat disediakan oleh pekerja. Dan tentu saja listrik, air dan tempat ini tidak pernah dimasukkan dalam komponen yang harus dibayar oleh perusahaan.
Tidak jelasnya hubungan kerja tentu menyulitkan pekerja apabila memiliki masalah atau sengketa. Tahun 2019 tertoreh sejarah mengenai hubungan kerja pekerja rumahan ini. Dalam putusan No. 26/Pdt.Sus/PHI/2018/PN Smg majelis hakim menyatakan pekerja rumahan (Giyati dan Osy Osela Sakti) dengan perusahaan (PT. Ara Shoes Indonesia) memiliki hubungan kerja.
Kesebelas, energi kotor yang merusak kehidupan. Perencanaan energi di Indonesia dilakukan melalui Perpres 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. Sedangkan untuk listrik diturunkan lagi melalui Rencana Umum Penyediaan Tenaga listrik. Dalam rencana pembangunan dinyatakan bahwa target pemerintah menyediakan energi ketenagalistrikan sebanyak 35.000 MW. Tentu saja itu bukan energi yang sedikit.
Ketersediaan energi ketenagalistrikan tentu memiliki kaitan erat dengan investasi, karena mereka membutuhkan jaminan dari pengurus negara, bahwa investasi di Indonesia akan lancar dengan dukungan pasokan ketenagalistrikan. Ada sebuah narasi yang menyatakan bahwa pengguna listrik terbesar adalah untuk kepentingan rumahtangga. Untuk melihat itu, mari kita bandingkan bagaimana beban penggunaan listrik? Beban penggunaan listrik tentu lebih besar di wilayah perkotaan dan wilayah kawasan industri, tentu untuk menjamin agar mesin produksi bisa berjalan 24 jam secara tidak terputus, menyalakan listrik-listrik di kompleks bisnis, perkantoran dan gedung-gedung pencakar langit termasuk hotel dan apartemen, lampu-lampu kota, papan reklame, lampu-lampu stadion, bisokop, departemen store dan pusat-pusat perbelanjaan maupun pusat-pusat hiburan. Berapa ribu watt listrik yang diperlukan untuk menjalankan seluruh aktifitas tersebut di atas jika dibandingkan dengan kebutuhan rumah tangga. Oleh karenya itu, nyata bahwa pasokan energi lebih banyak digunakan untuk kepentingan bisnis.
Di Indonesia, pemerintah masih menggunakan energi yang berasal dari fossil fuel, terutama untuk pembangkitan hampir sebagian besar menggunakan energi batubara. Batubara sendiri merupakan energi yang kotor. Kotor dalam banyak arti:
Menghasilkan polusi yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia;
Dalam tata kelola pertambangan dikelola oleh oligarki-oligarki yang hanya mengambil keuntungan untuk kelompoknya. Oligarki dalam bisnis pertambangan ini kemudian mempengaruhi kepada buruknya tata kelola pertambangan, ekonomi dan lingkungan hidup;
Merusak aspek ekologi baik di hulu maupun di hilir. di hulu pertambangan batu bara mengakibatkan rusaknya lingkungan, ekspansi lahan dan pencemaran terhadap masyarakat sekitar;
Sarat dengan tindakan-tindakan koruptif. Terutama dalam pemberian izin-izin pertambangan.
Pemerintah tidak memiliki strategi untuk mengembangkan penyediaan ketenagalistrikan yang beralih dari energi kotor ke Energi bersih dan terbarukan. Atau mendorong penyediaan energi ketenagalistrikan yang tidak menimbulkan krisis. Batubara merupakan energi yang tidak hanya kotor tetapi juga tidak terbarukan. Mayoritas pembangkitan energi kelistrikan di Indonesia menggunakan batubara. Setidaknya Indonesia cukup banyak membangun PLTU Batubara. Indonesia memang Negara yang memiliki garis pantai yang sangat panjang sehingga pembangunan PLTU batubara ini banyak dilakukan di wilayah pesisir. Walaupun saat ini juga mulai dikembangkan PLTU Mulut Tambang seperti halnya PLTU Mulut Tambang Riau 1. Di Riau sendiri tidak hanya PLTU Mulut Tambang Riau 1, tetapi Juga PLTU Tenayan Raya yang dibangun di aliran sungai SIAK. Sungai SIAK sendiri merupakan sungai yang menjadi Prioritas Nasional, dan bahkan statusnya tercemar. Pembangunan PLTU Batubara Tenayan Raya yang berada di aliran Sungai Siak akan menambah sumber pencemar.
Di Jawa Tengah, Pembangunan PLTU Batang dengan kapasitas 2×1000 MW mendapatkan penolakan dari Masyarakat. Warga bersama LBH Semarang pernah mengajukan gugatan ke PTUN atas diterbitkannya izin lingkungan untuk pembangunan PLTU tersebut. Hingga saat ini proses pembangunan PLTU Batubara di Batang terus berjalan. Begitu juga halnya dengan PLTU Celukan Bawang Bali, Pembangunannya bahkan tidak terencana dalam Rencana Umum Penyediaan Ketenagalistrikan (RUPTL). Namun pembangunan nya tetap berjalan. Warga mengajukan gugatan atas izin lingkungan pembangunan PLTU Batubara di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali. Gugatan tersebut didasarkan pada beberapa alasan diantaranya adalah karena alasan kesehatan, serta wilayah perairan Celukan Bawang merupakan wilayah konservasi laut. Begitu pula di Indramayu dan Cirebon, pembangunan PLTU Batubara diprotes oleh warga hingga berujung pada gugatan. LBH Bandung mendampingi warga untuk mengajukan gugatan atas pembangunan PLTU di Indramayu dan Cirebon.
Keduabelas, pembangunan geothermal.
Saat ini sudah 13 pembangkit listrik tenaga panas bumi sudah beroperasi. Sayangnya pembangunan Geothermal luput memperhitungkan masalah dan konflik yang ditimbulkannya. Konflik tersebut terjadi karena dua hal, pertama karena pembangunan tidak partisipatif dan kedua karena memberikan dampak lingkungan yang cukup serius bagi rakyat. Kasus tersebut misalnya di Gunung Slamet Jawa Tengah, Gunung Ciremai di Jawa Barat dan terakhir di Gunung Talang Sumatera Barat.
Dampak lingkungan yang serius tersebut di antaranya karena Operasional Geothermal membutuhkan banyak air, memungkinkan terjadinya penyerapan air yang sangat besar serta menimbulkan dampak berupa gempa minor.
PELANGGARAN HAM
Sepanjang tahun 2018, YLBHI bersama 15 LBH kantor melakukan pendokumentasian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dari kasus-kasus yang ditangani oleh 15 LBH kantor. Dari seluruh kasus yang ditangani oleh 15 LBH kantor Kami berhasil mendokumentasikan 380 kasus untuk diteliti pelanggaran HAM yang terjadi di dalamnya. Sebagian besar kasus mengandung lebih dari satu pelanggaran HAM oleh sebab itu jumlah keseluruhan pelanggaran HAM tidak sama dengan jumlah kasus.
Hasil pendokumentasian ini juga membuktikan keterkaitan dan interdependensi hak asasi manusia, bahwa ketika satu hak terlanggar hal itu menyebabkan pelanggaran hak lainnya juga dan hak sipil politik yang terlanggar menyebabkan terlanggarnya hak ekonomi atau sosial atau budaya dari korban yang sama, demikian juga sebaliknya. Misalnya, dalam banyak kasus terkait konflik lahan antara rakyat dengan negara/perusahaan selain melanggar hak atas lahan/tanah tetapi juga melanggar hak atas pekerjaan karena para petani terpaksa berganti profesi; hak atas standar hidup yang layak juga terlanggar dalam kasus Parangkusumo di Yogya ketika masyarakat terpaksa mengungsi ke tenda karena tanahnya telah dirampas; dalam beberapa kasus hal ini juga menyebabkan terlanggarnya hak atas kesehatan karena para korban terganggu kesehatan fisik maupun mentalnya; di kasus penggusuran Kampung Bobo di Manado walaupun hak utama yang terlanggar adalah hak atas tempat tinggal atau perumahan, beberapa anggota komunitas juga mendapat kesulitan mengurus identitas atau administrasi negara lainnya sehingga hak ekonomi, sosial, budaya berdampak juga pada pelanggaran hak sipil politik.
Hak atas peradilan yang adil
144
Hak atas pekerjaan. Termasuk hak atas upah layak, kondisi kerja yang sehat, hak untuk istirahat, liburan, pembatasan jam kerja yang wajar
142
hak kebebasan dan keamanan pribadi
48
Hak atas lahan/tanah
46
Hak atas tempat tinggal/perumahan
39
Hak kebebasan berekspresi termasuk untuk memperoleh informasi
30
Hak untuk bebas dari penyiksaan
30
Kekerasan/diskriminasi terhadap perempuan
29
Hak untuk hidup, termasuk standar hidup yang layak
23
Pembela HAM: Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif; hak untuk melakukan pekerjaan sosial
23
Hak untuk mendapatkan pelayanan umum tanpa diskriminasi
22
Hak atas lingkungan
22
Hak atas pembangunan
21
Hak atas kesehatan fisik dan mental
19
Hak atas ganti rugi atas pencabutan hak milik demi kepentingan hokum
18
Hak Anak
16
Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
16
Hak Berserikat/Berorganisasi
15
Hak untuk berkumpul dengan damai
10
Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil yang dipilih secara bebas. Hak ini termasuk untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, dan hak untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan atau usulan pada pemerintah.
10
Penikmatan hak tanpa diskriminasi
9
Hak untuk tidak dicampuri urusan-urusan pribadinya, keluarga, rumah, atau hubungan surat menyurat atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya
8
Hak untuk perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan atas urusan pribadinya
7
Hak untuk bebas dari ujaran kebencian yang mengarah pada permusuhan atau kekerasan
7
Hak atas pendidikan. Termasuk pendidikan dasar secara Cuma-Cuma
5
Hak atas pangan, termasuk bebas dari kelaparan, mendapatkan akses pada pangan
5
Hak atas budaya untuk kelompok minoritas, termasuk agama dan bahasa
4
Hak untuk menggunakan semua upaya hukum baik nasional dan internasional atas semua pelanggaran HAM yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional yang telah diterima Indonesia
4
hak masyarakat rentan untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan sesuai kekhususannya (affirmative action)
3
Hak menentukan nasib sendiri
3
Kekerasan/diskriminasi SOGIE
3
Hak untuk menikah dan membentuk keluarga
2
Hak untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya
2
Hak atas Jaminan Sosial
1
Hak atas kewarganegaraan termasuk identitas
1
Hak atas pemulihan apabila dilanggar haknya
1
Pelanggaran HAM masa lalu
1
Hak Disabilitas
1
Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum
1
Hak untuk tidak diperhambakan
1
Hak atas peradilan yang adil
Hak atas peradilan yang adil, kami bagi lagi menjadi beberapa hak turunan sebagai berikut:
Sebaran kasus di 3 wilayah:
Indonesia Barat (LBH Aceh, LBH Medan, LBH Padang, LBH Pekanbaru, LBH Palembang, LBH Lampung)
Indonesia Tengah (LBH Jakarta, LBH Bandung, LBH Yogyakarta, LBH Semarang, LBH Surabaya)
Indonesia Timur (LBH Bali, LBH Makassar, LBH Manado, LBH Papua)
Secara keseluruhan, hak atas peradilan yang adil dan hak atas pekerjaan menempati dua urutan teratas sebagai hak yang paling banyak terlanggar dengan pengecualian untuk kasus yang ditangani LBH di Indonesia Timur (LBH Makassar, LBH Manado, LBH Papua) hak atas pekerjaan lebih sedikit dibanding hak atas peradilan yang adil dan hak untuk bebas dari penyiksaan.
Hak atas peradilan yang adil kami detilkan lagi menjadi sejumlah hak untuk mengingat hak ini mencakup banyak hak turunan. Paling banyak adalah pelanggaran hak persamaan di depan hukum dan hak untuk tidak ditangkap sewenang-wenang. Data ini mencerminkan bahwa proses hukum di Indonesia masih banyak yang melanggar hak asasi manusia di berbagai tahapannya.
PELANGGARAN HAK ATAS KEMERDEKAAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN
Dari 15 kasus yang ditangani oleh YLBHI dan kantor-kantor LBH se-Indonesia terkait pelanggaran hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan (KBB), kasus yang paling banyak ditangani berbentuk larangan beribadah dan menggunakan tempat ibadah sebanyak 9 kasus. Bentuk-bentuk pelanggaran KBB lainnya antara lain; penyebaran kebencian, larangan berkumpul keagamaan, larangan ekspresi keagamaan, dan larangan pemakaman. Sebagian besar dari kasus-kasus tersebut terjadi di wilayah Jawa Barat. Ada paling tidak 9 dari 15 kasus terjadi wilayah itu.
PENYIKSAAN
Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan sejak 1998, praktik penyiksaan masih terus terjadi. Dari 29 kasus yang ditangani oleh YLBHI dan kantor LBH se-Indonesia, Kepolisian diduga sebagai pihak yang paling banyak melakukan, ada sekitar 27 kasus dimana Kepolisian diduga terlibat. Sementara pihak-pihak selain Kepolisian, seperti Tentara, Ormas, atau BUMD, diduga turut melakukan penyiksaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian. Bentuk-bentuk penyiksaan yang dilakukan, mulai dari pemukulan, penembakan, membakar dengan rokok, setrum, menyeret, menodongkan sejata api, mencambuk, melukai dengan senjata tajam, serta bentuk tindakan lain yang kejam, tida manusiawi, dan merendahkan martabat, seperti: meludahi, berdiri berjam-jam, menyiram air, berfoto, memaksa bernyanyi, larangan dijenguk, atau mata dilakban. Wilayah yang paling banyak menangani kasus penyiksaan adalah DKI Jakarta, ada sekitar 12 kasus tercatat ditangani di wilayah ini.
KRIMINALISASI
Selama tahun 2018, LBH Indonesia menangani 27 kasus kriminalisasi di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan jumlah korban 202 orang. Selengkapnya dalam infografis di bawah ini:
PENUTUP
Kesimpulan
Pelanggaran HAM menimpa nyaris semua orang (buruh, petani, miskin kota, perempuan, anak-anak, kelompok minoritas keagamaan, orang dengan orientasi seksual dan identitas gender berbeda) dan berdimensi luas mulai dari hak atas pekerjaan, hak atas tanah, hak atas peradilan yang fair, hingga kebebasan beragama dan hak atas privasi;
Kriminalisasi terhadap masyarakat terjadi hampir di seluruh sektor;
Pengembalian hak-hak masyarakat masih sebatas ilusi;
Atas nama pembangunan dan/atau kepentingan umum, hak rakyat dilanggar dan seiring dengan itu partisipasi masyarakat dilemahkan baik secara praktek berupa hanya pelibatan formil maupun di dalam perundang-undangan;
Pelanggaran hak atas pekerjaan didominasi oleh pemberangusan serikat buruh (union busting) dan upah;
Komitmen negara terhadap anti diskriminasi masih sebatas undang-undang karena diskriminasi terhadap orang yang dianggap berbeda terus terjadi. Ujaran kebencian yang kerap menjadi penyebab atau pencetus diskriminasi ini belum ditindak secara proporsional;
Hak atas kebebasan sipil dan keamanan pribadi warga terancam baik di tempat umum maupun di ruang privat. Berbagai alasan dapat menyebabkannya mulai karena melaksanakan kebebasan sipilnya, menjadi target diskriminasi maupun alasan lainnya;
Peradilan sebagai mekanisme pemulihan bukan hanya tidak bekerja, bahkan ikut menjadi bagian yang mencabut hak rakyat. Hal ini salah satunya bersumber dari hukum acara pidana yang bermasalah, korupsi pengadilan yang berakar dan ketiadaan pengawas eksternal yang memiliki cukup wewenang.
Proyeksi 2019
Pembangunan selain mengabaikan hak atas pembangunan rakyat juga dapat melenakan masyarakat dalam jangka pendek. Maka, korban-korban pembangunan akan berjatuhan kian banyak seiring dengan ketimpangan penguasaan aset;
Upaya pengambilalihan hak-hak rakyat di segala sektor akan terhambat oleh bersimpuhnya pemerintah dan aparat keamanan di bawah kuasa modal, maka kriminalisasi pun akan terus marak;
Peradilan akan terus menjadi alat penguasa dan pemodal serta menjauhkan pemenuhan HAM sebagai salah satu cita negara hukum:
Kriminalisasi, diskriminasi akan terus terjadi apabila hukum acara pidana khususnya tentang penahanan, pengendali perkara dalam penyidikan tidak segera diperbarui;
Impunitas terhadap pelanggaran HAM yang berat dan diskriminasi akan terus berlangsung selama Kejaksaan Agung tidak independen. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas keagamaan akan berlangsung terus selama fungsi kejaksaan mengawasi aliran kepercayaan di masyarakat tetap dijalankan.
Pengorbanan manusia oleh pengadilan akan terus terjadi apabila kemandirian hakim terus menjadi tameng korupsi peradilan;
Disinformasi melalui pemelintiran kebencian dengan mudah menempatkan siapapun yang dimauinya menjadi sasaran. Mendapatkan ruang pada pemilu, politik identitas yang ditopang oleh pemelintiran kebencian ini dapat menimbulkan luka berkepanjangan dan membelah masyarakat;
Dalam jangka panjang, apabila gejala-gejala ini tidak dihentikan dan diubah arahnya, Indonesia bukan tidak mungkin masuk dalam salah satu jebakan berikut: negara bangkrut, negara otoritarian baik oleh rezim militeristik ataupun rezim dominasi keagamaan tertentu. Hal ini hanya dapat dicegah apabila silent majority bergerak.